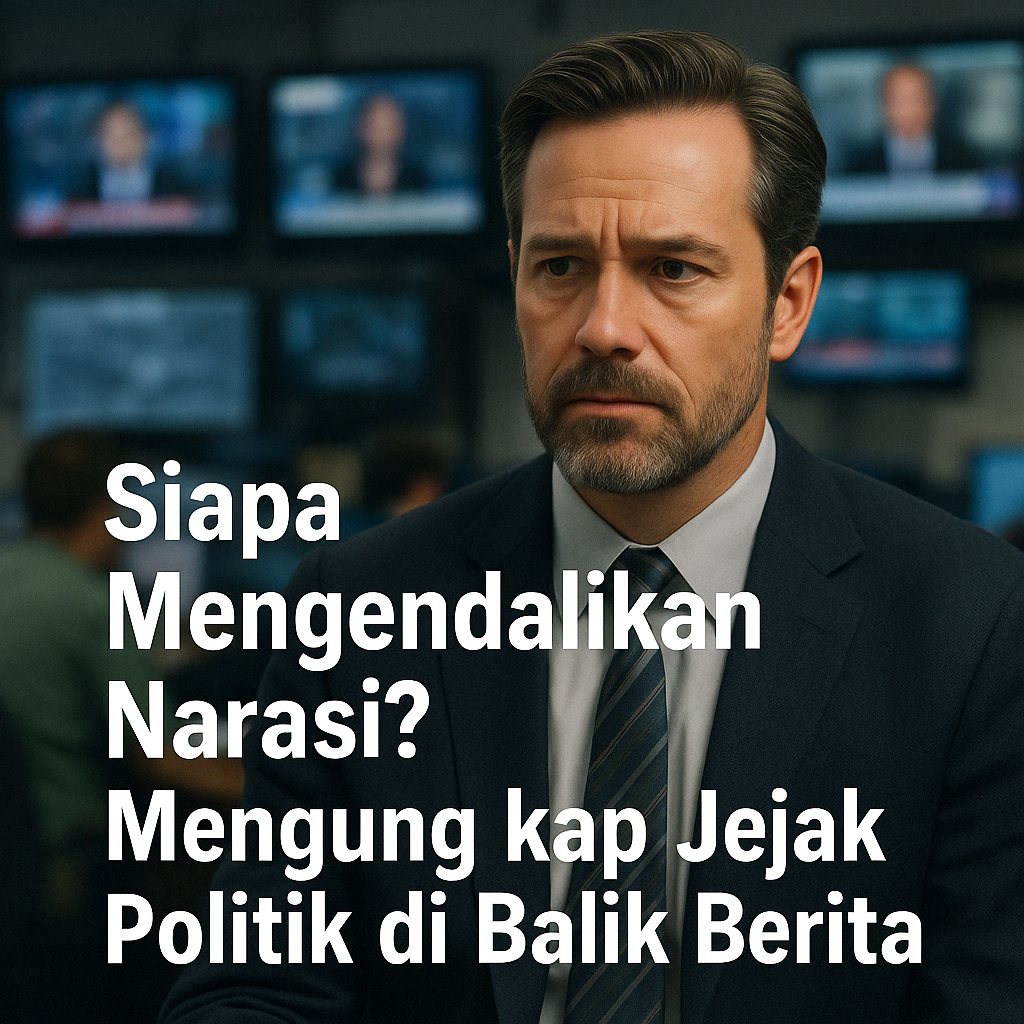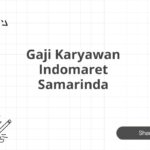Bahran – Di zaman serba digital ini, berita bukan lagi sekadar penyampai informasi. Ia telah berubah menjadi alat pengendali opini, pembentuk persepsi, bahkan pengarah kebijakan. Lalu, siapa sebenarnya yang berada di balik layar dan mengatur cerita-cerita yang setiap hari kita baca, tonton, atau dengar? Sejauh mana kepentingan politik memengaruhi isi berita yang tersebar?
Ketika Media Tak Lagi Netral
Dulu, media massa dipandang sebagai pilar keempat demokrasi—penjaga suara rakyat terhadap kekuasaan. Namun sekarang, media sering terseret dalam kepentingan politik dan bisnis. Di balik meja redaksi, tak jarang berdiri para pemilik modal, elit politik, hingga kelompok-kelompok berkepentingan.
Kontrol narasi tidak selalu dilakukan secara gamblang. Ia bisa tersembunyi dalam pemilihan kata, sudut pandang yang ditampilkan, atau isu yang diprioritaskan. Inilah alasan mengapa masyarakat harus berhenti menjadi konsumen pasif dan mulai menjadi pembaca yang kritis.
Politik Narasi: Saat Cerita Jadi Senjata
“Politik narasi” adalah istilah yang menggambarkan bagaimana cerita dikemas dan disebarkan untuk mendukung agenda tertentu. Narasi semacam ini belum tentu berisi kebohongan, tetapi sering kali hanya menampilkan sebagian dari kebenaran—yang sudah disaring, dibingkai, dan dikemas untuk menciptakan citra yang diinginkan.
Contohnya nyata dalam kampanye politik. Tokoh tertentu bisa digambarkan sebagai “harapan rakyat”, meski rekam jejaknya penuh tanda tanya. Dengan dukungan media, narasi itu bisa dibangun sedemikian rupa agar terlihat meyakinkan.
Ditambah lagi, kehadiran media sosial dan algoritma memperkuat kemampuan aktor politik untuk menyebarkan narasi ini secara masif dan terarah. Apa yang tampak sebagai suara publik sering kali hanyalah hasil manipulasi digital yang terencana.
Siapa di Balik Media?
Pertanyaan penting yang harus diajukan: siapa yang memiliki media? Di Indonesia, banyak media besar dimiliki oleh konglomerat yang juga terlibat di ranah politik atau bisnis besar lainnya. Kepemilikan semacam ini menimbulkan keraguan akan netralitas pemberitaan.
Media milik politisi, misalnya, cenderung menghindari berita yang bisa merugikan pemiliknya. Sebaliknya, media yang berseberangan akan lebih kritis terhadap pemerintah. Akibatnya, berita bukan lagi cermin realitas, tapi medan pertempuran narasi.
Media Sosial dan Fragmentasi Kebenaran
Era media sosial telah mengubah cara masyarakat mengonsumsi berita. Kini, semua orang bisa menjadi penyebar narasi. Ini membuka peluang partisipasi publik, tetapi juga membawa ancaman: hoaks, disinformasi, dan propaganda menjadi sulit dibendung.
Media sosial juga menciptakan “ruang gema”, di mana orang hanya terpapar informasi yang sejalan dengan pandangannya. Akibatnya, kebenaran menjadi terpecah. Dua pihak bisa memandang satu kejadian yang sama dengan tafsir yang bertolak belakang, tergantung dari narasi mana yang mereka konsumsi.
Politisi dan kelompok berkepentingan pun turut bermain. Mereka menyebarkan narasi melalui buzzer, bot, atau influencer. Hasilnya: dukungan semu yang dibangun di atas algoritma, bukan kesadaran publik.
Siapa yang Mendapat Untung?
Pengendali narasi biasanya adalah mereka yang punya kekuatan—baik secara politik maupun ekonomi. Mereka menggunakan berita untuk mempertahankan kekuasaan, memoles citra, dan meredam kritik.
Namun, di balik hegemoni itu, muncul juga suara-suara alternatif: dari jurnalis independen, media rakyat, hingga organisasi masyarakat sipil. Meski kecil, mereka berjuang merebut ruang narasi lewat liputan investigatif, analisis mendalam, dan advokasi digital.
Platform seperti Portal Narasi adalah contoh bagaimana wacana tandingan bisa tumbuh. Dengan menyoroti isu yang luput dari perhatian media arus utama, mereka mengajak publik melihat dari sudut pandang yang lebih luas dan adil.
Literasi Media Adalah Kunci
Di tengah derasnya arus informasi, kemampuan memilah dan memahami berita menjadi senjata utama. Literasi media bukan cuma soal bisa baca berita, tapi juga soal memahami siapa yang menulisnya, kenapa ditulis, dan bagaimana ia disusun.
Berikut beberapa cara sederhana untuk meningkatkan literasi media:
- Periksa sumbernya: Apakah medianya kredibel? Apakah ada afiliasi politik atau ekonomi?
- Baca dari berbagai sumber: Bandingkan berita yang sama dari media yang berbeda.
- Hindari terjebak judul provokatif: Banyak berita dibuat sensasional hanya demi klik.
- Gunakan alat verifikasi: Seperti Google Fact Check atau Turn Back Hoax.
- Diskusikan isu dengan orang lain: Sudut pandang berbeda memperkaya pemahaman.
Menuju Media yang Lebih Sehat
Media seharusnya jadi cermin aspirasi rakyat, bukan corong kekuasaan. Untuk mencapainya, perlu dukungan sistemik: dari regulasi yang adil, transparansi kepemilikan media, hingga pendidikan literasi media sejak usia dini.
Langkah-langkah nyata yang bisa dilakukan antara lain:
- Transparansi kepemilikan media agar publik tahu siapa di balik layar.
- Dukungan terhadap media independen, baik melalui donasi, subsidi negara, atau model crowdfunding.
- Pendidikan literasi media di sekolah agar generasi muda lebih kritis.
- Penguatan etika jurnalistik demi menjaga akurasi dan keberimbangan informasi.
Penutup: Narasi Adalah Kekuatan
Narasi bukan sekadar cerita—ia adalah alat kekuasaan. Siapa yang menguasai narasi, mampu membentuk persepsi, memengaruhi opini, bahkan mengarahkan masa depan.
Di tengah kebisingan informasi, kebenaran tidak selalu mudah ditemukan. Ia tersembunyi di balik kepentingan, framing, dan algoritma. Maka dari itu, tugas kita adalah menjaga ruang publik tetap sehat, terbuka, dan jujur.
Dengan terus mengasah literasi media dan mendukung sumber informasi yang independen, kita ikut menciptakan masyarakat yang sadar, kritis, dan tidak mudah dimanipulasi. Bukan hanya untuk hari ini, tapi demi demokrasi yang lebih kuat di masa depan.